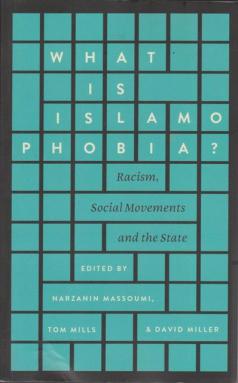 Judul Buku: What Is Islamophobia?
Judul Buku: What Is Islamophobia?
Editor : Narzanin Massoumi, Tom Mills & David Miller
Penerbit : Pluto Press, London
Tebal : xiv + 286 halaman
Cetakan : Pertama, 2017
Islamofobia sebenarnya bukan gejala baru di dunia. Gejala ini sudah tampak ratusan tahun lampau dan menghinggapi wilayah geografis yang luas. Hanya saja, belakangan, gejala tersebut meningkat tajam usai tragedi 9/11 di New York, AS. Kian banyak orang di Barat, terutama dari kalangan politisi dan elit pemerintahan, yang curiga terhadap komunitas atau kelompok-kelompok Islam. Ditambah lagi, munculnya al Qaeda serta ISIS yang mengusung ideologi kekerasan.
Bagi media Barat, ideologi ini merupakan topik panas sehingga membentuk tipologi tunggal, bahwa Islam merupakan agama kekerasan. Ketidakpahaman terhadap Islam serta realitas spektrum muslim juga menjadi faktor lain dari menguatnya Islamofobia ini. Para pengambil kebijakan minim wawasan kemudian terjebak ke dalam kecenderungan Islamofobia. Mereka mengabaikan realitas kemajemukan muslim dan sikap antipati sebagian besar muslim pada ideologi kekerasan. Bahkan diantara mereka pun berpendapat, Islam merupakan agama teror dan para muslim punya kecenderungan menjadi teroris. Selama bertahun-tahun, sejak tragedi 9/11, stereotyping demikian berlangsung dari hari ke hari. Memunculkan situasi anti-muslim di negara-negara Barat, yang pelan-pelan merembes ke negara-negara Asia.
Buku ini merupakan hasil pengembangan materi konferensi ‘Understanding Conflict’ yang digelar di Universitas Bath pada Juni 2015. Terdapat 13 kontributor yang ikut menyumbangkan materi dalam konferensi yang tulisannya dihimpun dalam buku ini. Editor buku membagi tulisan-tulisan itu ke dalam empat bagian.
Pada bagian pertama merupakan perkenalan tentang apa itu Islamofobia, yang ditulis oleh tiga editor buku. Bagian kedua bertajuk ‘Islamofobia, Kontra-Terorisme dan Negara’ yang berisi tulisan-tulisan untuk memetakan sekaligus menghubungkan antara program ‘Perang Lawan Teror’ dan naiknya arus Islamofobia. Bagian ketiga merupakan kumpulan tulisan di bawah judul besar ‘Gerakan Sosial Dari Atas’ berisi tulisan pemetaan bagaimana pengarus-utamaan Islamofobia berlangsung dari suprastruktur kekuasaan. Dan bagian keempat, beberapa tulisan bernaung di bawah tajuk ‘Melawan Kembali’. Dari rangkaian bagian dalam buku ini, bisa diketahui upaya untuk menyuguhkan sebuah pemahaman utuh kenapa Islamofobia menguat dan kaitannya pada wacana ‘Perang Lawan Teror’.
Di awal pembahasan, editor buku ini sudah menegaskan bahwa Islamofobia bukanlah sekadar produk sebuah proses ideologi, melainkan ia merupakan aksi sosial nyata yang sedang berlangsung dengan tujuan tertentu. Penegasan ini membedakan kerangka acuan baik editor maupun seluruh penulis dalam buku ini, dari buku atau karya tentang Islamofobia yang sudah ada sebelumnya.
Dalam catatan editor, terdapat lima pilar atau aktor yang secara aktif berada di balik aksi-aksi sosial bernuansa Islamofobia. Pengertian aktor disini bisa berupa orang atau institusi. Pertama, aktor itu adalah negara yang melahirkan aparat untuk program ‘Perang Lawan Teror’. Kedua, gerakan neo-konservatisme yang merupakan bagian dari gerakan Zionisme internasional. Ketiga, gerakan kontra-jihad yang marak di berbagai belahan dunia. Gerakan kontra-jihad ini kerap bersinergi dengan kelompok nasionalisme-fasis. Keempat, elemen-elemen liberal, Kiri dan sekular yang mewujud dalam berbagai organisasi. Kelima, gerakan feminisme yang juga marak serta aktif di berbagai lini kemasyarakatan.
Oleh karena itu, menteorisasikan Islamofobia menjadi sangat perlu. Untuk itu, editor buku lebih dulu meninjau penolakan sejumlah intelektual terhadap istilah ‘Islamofobia’. Termasuk penolak itu adalah Fred Halliday, intelektual sohor pakar Timur-Tengah. Fred beralasan, istilah Islamofobia kurang tepat, sebab kenyataan menunjukkan yang menjadi target kebencian rasial adalah muslim secara personal. Bukan pada agama. Sebaliknya, Fred menawarkan istilah ‘anti-Muslimisme’. Sanggahan Fred ini diikuti oleh kaum liberal, Kiri dan pengusung nasionalis-fasis.
Sedangkan, para pengkampanye anti-rasis justru melihat Islamofobia merupakan dampak dari rasisme. Namun, kaitan antara Islamofobia dan rasisme masih sulit dijelaskan, hingga para sosiolog anti-esensialisme mengungkap ihwal konsep ‘rasialisasi’. Bahwa, jika ‘ras’ merupakan fiksi yang diciptakan untuk menunjuk pada etnik dengan warisan budaya serta praktek budaya yang pada gilirannya etnik tersebut merasakan keuntungan atau kerugian, maka secara ontologis (keberadaan sesuatu yang bersifat kongkret) identitas keagamaan tidaklah berbeda dari ‘ras’. Sehingga, rasialisasi yang meningkat bisa digunakan untuk menilai bahwa Islamofobia merupakan bentuk dari rasisme.
Sayangnya, survei literatur seputar kondisi rasialisasi ini menunjukkan isu Islamofobia amat jarang dimasukkan. Baru belakangan, sejumlah intelektual seperti Meer, Modood dan Vakil justru menyodorkan kenyataan rasisme budaya yang didalamnya mengandung pula sikap anti-Islam dan anti-muslim. Oleh karena itu, rasisme budaya tidak bisa hanya dipandang sebagai cerminan rasisme biologis belaka, sebab ada elemen-elemen anti-muslim dan anti-Islam didalam sikap rasis tersebut. Masalahnya kemudian, seringkali perbincangan soal ras dan proses rasialisasi ini mengabaikan aktor dan gagasan yang meningkatkan rasialisasi. Oleh karenanya, penulis buku ini juga menyoroti posisi aktor serta gagasan yang diproduksinya.
Pada kasus Islamofobia, para aktor pencetusnya meletakkan Islam dalam arena politik. Dalam kaitan ini, Islamofobia yang merupakan bentuk rasisme bukan saja berhubungan pada aksi kelompok dalam struktur masyarakat, melainkan juga berlangsung ketika terjadi transformasi di dalam masyarakat itu. Berbagai kebijakan serta program ‘Perang Lawan Teror’, program ‘deradikalisasi’ dan sejenisnya, akan segera tampak sebagai upaya Islamofobia yang diprakarsai oleh aparat negara secara berkesinambungan.
Tak berlebihan jika para penulis buku ini mengatakan bahwa saat ini tengah berlangsung rasisme struktural. Bentuk rasisme ini bukan muncul dengan sendirinya di dalam masyarakat, namun secara sengaja direkayasa oleh aparat negara. Mirip seperti apa yang dituliskan dalam karya klasik Edward Said bertajuk ‘Orientalisme’, bahwa sikap-sikap penuh prasangka serta kecurigaan selalu diarahkan kepada kelompok yang telah dilabeli ‘ekstrem’, ‘intoleran’, atau ‘radikal’. Tanpa ada penelitian memadai, label ini dipertahankan terus untuk menjaga struktur serta rasionalisasi kebijakan sarat Islamofobia.
Dari sinilah kita melihat, betapa kajian-kajian pasca-struktural memang telah menyediakan pisau analisa yang sangat tajam untuk membedah kenapa Islamofobia saat ini tak lain adalah bentuk rasisme. Melalui adanya struktur sosial yang direkayasa via pelabelan terlebih dulu. Enam artikel yang ditulis oleh sepuluh penulis pada bagian ketiga dalam buku ini yang bertajuk ‘Gerakan Sosial Dari Atas’ layaknya penegas, bahwa Islamofobia (rasisme struktural) secara sengaja dilakukan para aktor negara demi tujuan-tujuan politik tertentu.

