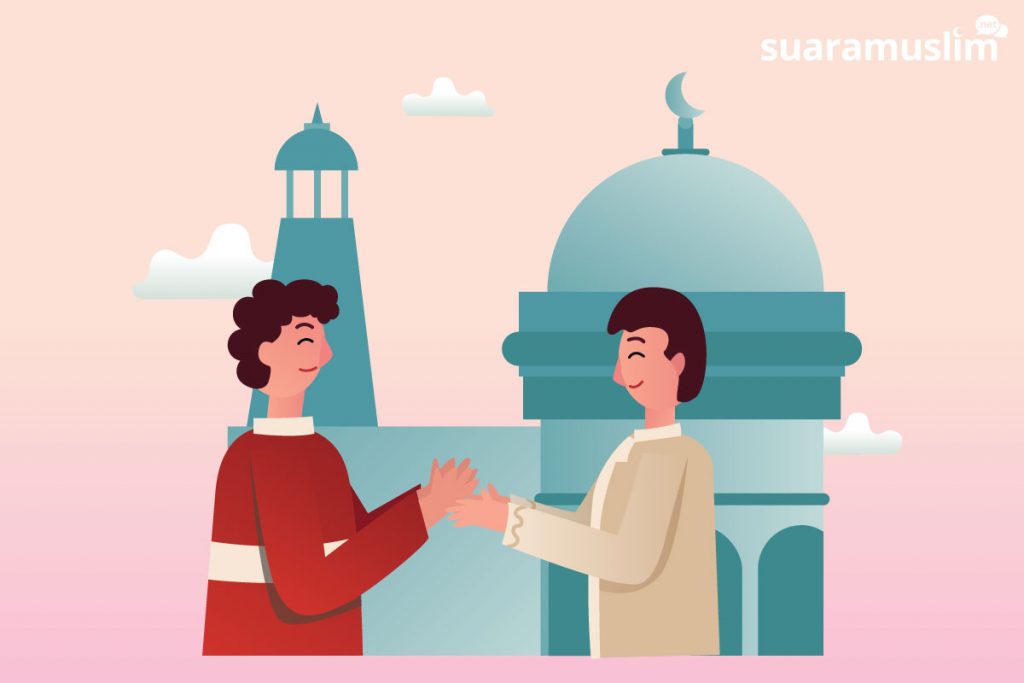Suaramuslim.net – Saya membacanya pelan-pelan. Surah Al-Furqān, ayat 63 sampai 77. Tidak bisa cepat. Ayat-ayat ini seperti cermin. Kalau dibaca cepat, apalagi tergesa-gesa, wajah kita tidak sempat tampak jelas.
Di ayat ini Allah sedang memotret tipe manusia. Bahkan memberi nama dengan nama yang indah, yaitu: ‘Ibadur-Raḥman, hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih.
Ayat 63 berbunyi begini: “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati…” (QS. Al-Furqān: 63).
Ayat ini memulai menyebut ciri pertama ‘Ibadur-Rahman dari “cara berjalannya di bumi”.
Artinya bagaimana kita membawa diri di tengah orang lain dengan “rendah hati”. Di kantor. Di kampung. Di jalan. Di grup WhatsApp. Di media sosial, dan di manapun di muka bumi ini.
Rendah hati itu bukan merendah di depan atasan lalu meninggi di depan bawahan. Bukan juga diam saat benar demi aman atau karena takut. Rendah hati itu artinya tahu diri. Sadar posisi. Tidak merasa langit runtuh kalau pendapatnya dikritik.
Lalu ayat itu dilanjutkan dengan kalimat yang, kalau dibaca saat ini, terasa sangat “era now”:
“Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang damai” (QS. Al-Furqān: 63).
Menarik sekali. Tidak disebut “membungkam”. Tidak juga “mengalahkan”. Tetapi damai, menenangkan.
Di zaman kini ketika orang berlomba memenangkan debat tetapi lupa menjaga adab, ‘Ibadur-Raḥman memilih tetap waras.
Setelah bicara tentang interaksi sosial di siang hari, ayat selanjutnya masuk ke wilayah yang sangat pribadi, yaitu: malam. Ayatnya: “Dan orang-orang yang menghabiskan malamnya untuk Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.” (QS. Al-Furqān: 64).
Ayat ini menegaskan betapa pentingnya salat malam, tahajjud. Meskipun hukumnya sunnah, tapi pasti bukan sunah biasa. Salat tahajjud adalah soal hubungan tulus dan terbuka dengan diri sendiri dan Allah. Orang yang bangun malam biasanya tidak sedang ingin dilihat. Tidak sedang ingin dipuji. Karena tidak ada siapa-siapa. Bahkan kamera pun tidak menyala.
Tahajud itu tempat manusia meletakkan semua topengnya. Di siang hari kita biasanya sibuk menjelaskan tentang banyak hal kepada manusia. Di malam hari, ‘Ibadur-Raḥman menjelaskan dirinya kepada Tuhan. Sambil berdoa secara sungguh-sungguh: “Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab neraka…” (QS. Al-Furqān: 65).
Ini doa orang yang sadar: amalnya belum tentu cukup. Jabatan tidak menjamin. Popularitas juga tidak.
Lalu pada ayat berikutnya Al-Qur’an Surah Al-Furqān ini bicara tentang tiga hal yang paling sering menjatuhkan manusia. Apa itu: teologi, kekuasaan, dan nafsu. Ayatnya begini: “Mereka tidak menyembah selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan tidak berzina.” (QS. Al-Furqān: 68).
Dan ini yang luar biasa. Ternyata Allah tidak kejam. Allah tidak memakukan manusia pada masa lalunya. Di ayat berikutnya, Allah membuka pintu yang sangat manusiawi: “Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh…” (QS. Al-Furqān: 70).
Ini penting. ‘Ibadur-Raḥman bukan manusia bersih dari kesalahan. Mereka bisa saja pada masa lalunya penuh dosa. Tetapi mengambil jalan untuk bertobat. Bahkan Allah seolah memberi bonus besar kepada mereka yang masa lalunya pendosa lalu bertobat, yaitu dengan menggantikan semua keburukan amalnya dengan kebaikan.
Dan itulah cara Allah menunjukkan sifatnya bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan kepada pezina sekalipun asal mereka bertobat (QS. Al-Furqān: 70).
Kemudian ada satu ayat pendek yang rasanya seperti teguran bagi ruang publik kita hari ini: “Dan mereka tidak memberikan kesaksian palsu.” (QS. Al-Furqān: 72).
Kesaksian palsu bukan hanya di pengadilan. Bisa saja itu terjadi dan dilakukan dalam laporan yang dimanipulasi. Data yang diatur ulang. Narasi yang dipelintir demi kepentingan. Di titik ini, ‘Ibadur-Raḥman memilih jalur terang, yaitu: tetap jujur meski mungkin untuk sebagian orang jujur itu tidak mengenakan.
Soal harta, Allah kembali menaruh standar kewarasan: “Apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir.” (QS. Al-Furqān: 67).
Bukan boros demi pencitraan (pamer). Bukan pelit demi rasa aman. Hidup secukupnya ternyata adalah ajaran spiritual yang matang.
Puncaknya adalah doa yang sangat menyentuh: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata…” (QS. Al-Furqān: 74).
Ini bukan doa orang yang egois. Ini doa orang yang berpikir jauh melampaui dirinya sendiri. Orang boleh sukses sendirian. Tetapi ‘Ibadur-Raḥman ingin keluarganya ikut selamat. Nilainya diwariskan. Kebaikannya berumur panjang.
Pertanyaannya: masih masuk akalkah semua ini di era yang serba cepat dan gaduh? Jawabannya “sangat masuk akal”.
Justru sekarang. Di era bising, tahajud menjadi ruang pendingin. Di era emosional, kerendahan hati menjadi kekuatan. Di era pamer, ketulusan menjadi kemewahan.
Menjadi ‘Ibadur-Raḥman hari ini bukan berarti menyingkir dari dunia. Tetapi menjalani dunia tanpa kehilangan arah batin. Mungkin di antara kita ada yang merasa belum sampai. Tidak apa-apa. Al-Qur’an tidak sedang mencoret nama. Ia sedang membuka pintu. Mengundang, bukan menghakimi.
Karena menjadi ‘Ibadur-Raḥman bukan soal klaim. Tetapi tentang hidup yang jika suatu hari nama kita disebut, Allah menyebutnya dengan kasih, bukan dengan murka.
Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur