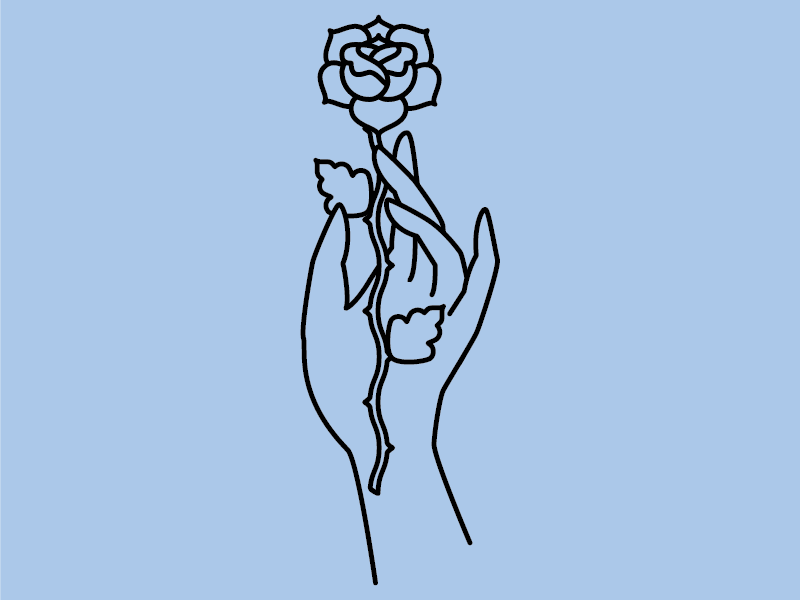Diabolisme Intelektual dari Rahim UIN
Di penghujung tahun 1440 Hijriah, saat kaum muslimin bersuka cita menyambut tahun baru 1441 Hijriah, muncul pemikiran sesat yang menyatakan bahwa hubungan seks non-marital dengan pendekatan konsep milkul yamin dibolehkan secara syariah. Pemikiran yang semula digagas oleh Muhammad Syahrur, dari Suriah itu, telah mengundang polemik dan penolakan karena oleh Abdul Aziz dijadikan disertasi, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
“Penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep milk al yamin Muhammad Syahrur merupakan sebuah teori baru yang dapat dijadikan sebagai justifikasi terhadap keabsahan hubungan seksual nonmarital. Dengan teori ini, maka hubungan seksual nonmarital adalah sah menurut syariah sebagaimana sahnya hubungan seksual marital. Dengan demikian, konsep ini menawarkan akses hubungan seksual yang lebih luas dibanding konsep milk al yamin tradisionalis.”
Itulah kesimpulan disertasi yang berjudul, “Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual non Marital.” Ditulis oleh Abdul Aziz, mahasiswa program doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Sayangnya pihak UIN Jogja, kemudian meloloskan disertasi itu dan memberikan gelar doktor kepada Abdul Azis. Seharusnya para pembimbing dan penguji dapat mengarahkan disertasi Abdul Azis sebagai antitesa, bukan sebaliknya malah melegitimasi dan menjustifikasi (tabriri) pemikiran Muhammad Syahrur, yang sangat jelas kesesatannya.
Al-Qur’an menyebut frasa milkul yamin dalam pengertian kepemilikan tangan kanan, hamba sahaya atau budak, sebanyak 15 kali. Dalam konteks ayat melekat perintah berlaku adil dalam perkawinan (QS. 4:3, 24, 25, 36, dan QS. 24:33, QS. 33:50, 52), pembagian rezeki yang sebanding (QS. 16:71, QS 30:28), dan menjaga aurat dari pandangan mereka, bahkan melarang budak memasuki kamar pada tiga waktu yang ditetapkan (QS. 24:31, 58, QS. 33:55).
Sedangkan ayat yang selalu dikutip, QS 23:6, baik oleh Syahrur maupun Azis, hanya dipahami sebagai budak yang terikat haknya secara fisik, termasuk dalam hal hubungan seksual. Dan lebih sempit lagi definisi itu hanya berlaku pada budak perempuan.
Dalam al-Qur’an memang terdapat ayat yang membolehkan seorang laki-laki menggauli budak perempuannya. Tanpa akad nikah. Seperti pada surat al-Ahzab: 50, an-Nur: 31 dan al-Mukminun: 5-6.
“Dan orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.” (Q.S. 23:5-6).
Hari ini tidak ada lagi perbudakan. Karena itu kemudian Syahrur menganalogikan kebolehan menggauli budak ini dengan jenis hubungan seksual yang tidak normal lainnya. Seperti nikah mut’ah, nikah muhalil, nikah misyar (kawin kontrak) bahkan samen leven(kumpul kebo). Karena hari ini tidak ada lagi budak, maka seorang laki-laki boleh menggauli perempuan bukan budak tanpa menikah. Cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian kumpul kebo pun sah secara syariah.
Itulah jurus akrobatik Muhammad Syahrur yang diamini Abdul Aziz. Tanpa kritik yang berarti. Bahkan si penulis disertasi menyayangkan Syahrur yang hanya membuka pintu seks bebas dengan kedok milkul yamin hanya untuk laki-laki.
Ia menyatakan, “Namun, ditinjau dari perspektif emansipatoris, ekstensitas akses seksual dalam konsep ini masih tampak timpang, karena hanya dapat dinikmati oleh laki-laki sementara bagi perempan cenderung stagnan.” Inna lillahi wal ‘iyadzu billah.
Menjadikan milkul yamin sebagai pembenaran seks luar nikah jelas sesat dan menyesatkan. Memperluas makna milkul yamin kepada selain budak rampasan perang adalah pembodohan sekaligus kejahilan yang berlipat ganda (murakkab).
Tesis utama Syahrur, al-Qur’an turun sebagai pedoman untuk semua manusia dan sepanjang masa, karena itu harus bisa disesuaikan dengan cara hidup apa pun dan di mana pun. Maka Alquran harus sesuai, disesuaikan dan dipaksa sesuai.
Dalam kasus ini, karena seks di luar nikah sudah lumrah di banyak tempat, maka al-Qur’an harus menyesuaikan diri. Inilah yang mereka sebut, Islam itu rahmatan lil ‘alamin, sehingga kerusakan moral pun hendak dibenarkan dengan dalih syariat Islam cocok untuk segala kondisi dan tempat. Bedanya, jika Islam menghendaki aturannya diterapkan tanpa mengubah substansi dan bentuk hukuman, maka kaum liberalis munafikin menginginkan syariat Islam tunduk kepada dinamika sejarah dan budaya manusia.
Yang pertama menyatakan bahwa syariat Islam ini otentik, sempurna dan sudah final, maka yang diperlukan adalah langkah-langkah devolutif. Sementara yang kedua menyatakan bahwa syariat Islam ini masih jauh dari final dan sempurna, karena harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika sejarah dan sosial budaya manusia, sehingga bersifat evolutif. Itulah jenis Islam baru yang dipropagandakan kaum liberal model Muhammad Syahrur.
Hermeneutika al-Qur’an Syahrur terlihat dominan menggunakan teori hermeneutika Paul Ricoeur, yakni dekontekstualisasi ketika materi teks berlepas dari cakrawala intensi yang terbatas dari pengarangnya, serta membuka teks dibaca secara luas dengan pembaca beragam atau rekontekstualisasi.
Ini artinya Syahrur anti otoritas keilmuan, sehingga sesuatu yang qath’i (pasti) bisa jadi zhanni (asumtif) dan begitu sebaliknya. (Baca artikel “Otoritas Keagamaan” dalam buku Islam dan Diabolisme Intelektual karya Dr Syamsudin Arif, hlm. 34-40).
Dari hasil buah pikirannya Syahrur jelas bukan ulama otoritatif, dia hanya seorang pembaca yang keluar dari framework dan worldview Islam, serta terpengaruh atau bahkan ‘mengimani’ framework dan worldview Barat.
Contohnya: a) Berpandangan bahwa meski al-Qur’an adalah wahyu dan mukzijat, namun sejatinya manusia itu sendiri yang membuat mukjizat melalui kedinamisan penafsiran; b) al-Qur’an itu makhluk, bukan kalam Allah; c) lafadz al-Qur’an tidak memiliki sinonim (muradif); d) as-Sunnah katanya bukan wahyu; e) manusia zaman modern lebih matang dalam membuat hukum ketimbang para Nabi; f) Islam itu katanya mendahului Iman, sehingga bisa saja ada muslim kristen, muslim yahudi dll, jelas pandangan pluralisme Barat dia gunakan; g) penggalian hukum Islam mesti disesuaikan dengan realitas masa kini, artinya hukum Islam mesti tunduk pada realitas, dan bukan sebaliknya realitas tunduk pada hukum Islam.
Tidak mengejutkan, ketika hubungan seksual non-marital (kumpul kebo) dilegalkan Syahrur, sebab ini bukan berdasarkan dalil, namun karena pasrah pada kenyataan seksualitas yang banal di Barat, karena dia terpapar HAM Barat yang permisif sekaligus primitif. Sungguh ironis, padahal dalam hukum Islam dasar keharaman zina sudah jelas.
Adapun pemberian batasan atau limit bagi kategori kegiatan seks itu zina atau bukan, sebagaimana yang dinyatakan Azis, “Ada berbagai batasan atau larangan dalam hubungan seks nonmarital yaitu dengan yang memiliki hubungan darah, pesta seks, mempertontonkan kegiatan seks di depan umum, dan homoseksual,” maka itu tidak mengubah sama sekali posisi dasar hukum zina (hubungan seks di luar nikah) yang diharamkan dalam Islam dengan hukuman badan yang keras, yaitu 100 kali cambuk bagi lajang (Q.S. 24:2) atau rajam sampai mati bagi yang sudah menikah (Muttafaq ‘alaih). Karena jika batasan atau larangan versi Azis itu pun dilanggar, maka hukumannya semakin berat dari hukum asal perzinaan.
Peran Ulama
Inilah bahayanya jika umat Islam dan para ulama kendor dalam menjalankan fungsi amar makruf nahi munkar dalam bidang akademik. Dengan dalih kebebasan ilmiah, seseorang bisa dengan mudah mengotak-atik dan membongkar syariat Islam semaunya, lalu mendakwa dirinya sebagai pembaharu. Na’udzu billah.
Sudah saatnya para ulama lintas ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia turun tangan menindaklanjuti fatwa haram Liberalisme, Sekularisme dan Pluralisme agama yang telah disahkan pada Munas MUI tahun 2005 silam.
Sudah 14 tahun fatwa itu keluar, entah kini bagaimana nasibnya? Apakah umat Islam dan para ulama masih peduli terhadap keberlangsungan dan tindak lanjut fatwa itu dalam kondisi kita yang seperti ini? Semoga harapan itu masih ada. Wallahu a’lam bil-shawab.
Jakarta, 3 Muharram 1441 H
Fahmi Salim
Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI & Majelis Tabligh PP Muhammadiyah