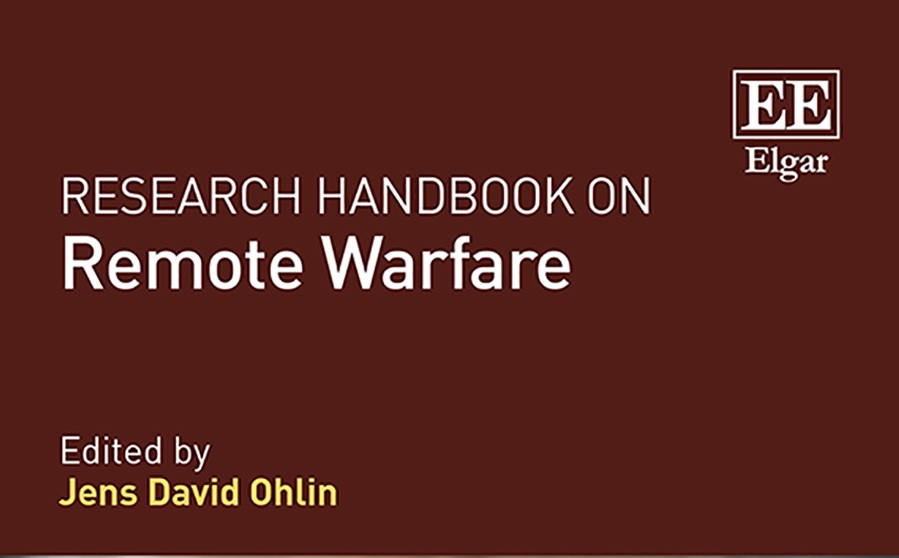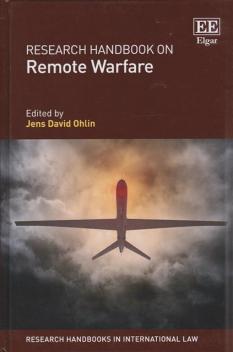 Judul Buku: Research Handbook on Remote Warfare
Judul Buku: Research Handbook on Remote Warfare
Editor : Jens David Ohlin
Penerbit : Edward Elgar, UK
Tebal : xxii + 501 halaman
Cetakan : Pertama, 2017
Suaramuslim.net – Arena pertempuran sudah berubah seiring perubahan teknologi siber. Teknologi satu ini punya daya jangkau lebih luas berdampak lebih masif. Jika dulu arena perang berada di lokasi-lokasi tertentu, maka kini perang bisa dikendalikan dari jauh. Aktor-aktor perang tak perlu hadir di lapangan, cukup memonitor dari jauh lewat perangkat remote yang kian canggih. Hukum perang yang semula melekat pada manusia, kini mulai banyak dipertanyakan. Bagaimana jika yang hadir di lokasi perang atau tempat penyerangan itu adalah mesin? Yang mungkin tak diketahui siapa pengendali mesin itu? Siapa yang bertanggung-jawab atas dampak perang akibat mesin yang diprogram jarak jauh tersebut? Pertanyaan-pertanyaan macam ini menyeruak saat para ahli strategi perang mulai melihat begitu gencar industri militer mengembangkan teknologi siber serta pengendalian jarak jauh, dengan alasan demi efektivitas serta efisiensi dalam perang. Perkara perang bukan lagi sebatas perkara kepentingan atau beda ideologi, tapi di dalamnya sudah ada semangat efektivitas serta efisiensi. Dua kata kunci dalam kamus neoliberal. Alasan yang sulit dibantah, perang merupakan peristiwa ekonomi biaya tinggi, sehingga perlu dicari solusinya, dan pilihan paling memungkinkan hanyalah lewat pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh.
Buku ini kumpulan tulisan 20 pakar di bidang hukum internasional, hukum militer serta guru besar di bidang hukum dari Inggris, Jerman, Belanda, AS, Kanada serta Australia. Mereka dipertemukan oleh satu kesamaan, yakni memfokuskan diri pada aspek sekaligus dampak hukum atas pengendalian jarak jauh. Masyarakat internasional sadar atau melek hukum tentu telah mempertanyakan, misalnya, bingkai hukum atas operasi perang memakai drone. Pesawat nirawak ini sudah biasa dipakai militer AS dan beberapa negara Eropa untuk mencari sekaligus menewaskan target-target tertentu. Memang, sudah ada perangkat hukum HAM internasional atau hukum humaniter internasional, namun piranti hukum tersebut melekat pada manusia, bukan mesin.
Bahkan sejak heboh virus Stuxnet beberapa tahun silam ditambah juga kecurigaan intervensi siber dari Rusia ke proses Pilpres AS pada 2016, lalu muncullah apa yang disebut sebagai ‘Tallin Manual‘. Panduan hasil konferensi diprakarsai pusat kerjasama pertahanan siber NATO di Eropa. Dalam panduan yang mulai tersebar pada 2017 ini, teknologi siber disorot dari berbagai perspektif hukum. Diantaranya, hukum siber untuk pertahanan dan keamanan, lalu juga hukum telekomunikasi internasional, hukum udara, hukum angkasa luar, hukum laut serta hukum diplomatik dan konsuler. Namun demikian, sampai saat ini perhatian utama para pakar hukum tetap pada cara serta upaya penerapan norma-norma hukum siber internasional untuk kepentingan praktis.
Ada tiga agregat dalam amatan para penulis buku ini. Ketiganya mencakup drone, siber serta ‘Autonomous Weapons System’ (AWS). Ketiga agregat ini disatukan oleh wacana pengendalian jarak jauh (remote). Kapabilitas remote inilah yang telah mengubah paradigma perang abad 21. Lokasi perang yang jauh bukan lagi halangan untuk menjangkau sasaran-sasaran teridentifikasi. Apalagi, kapabilitas sistem persenjataan otonom mampu mengirim pesawat nirawak, baik untuk memata-matai atau untuk menembak langsung. Begitupula pada serangan siber. Serangan ini kenyataannya bisa dilakukan lintas negara. Virus komputer yang dikembangkan sedemikian rupa bisa diinjeksikan ke dalam sistem komputer lawan secara diam-diam.
Sedangkan sistem persenjataan otonom yang akrab disebut ‘AWS’, meliputi robot-robot mematikan. Robot ini juga dikendalikan jarak jauh. Ia menerima komando dari operator yang menjalankannya di pusat-pusat kendali. Dari sini timbul situasi yang berbeda dari perang biasa. Jika di masa lalu, warga sipil mudah jadi korban, maka setelah teknologi drone digunakan korban warga sipil bisa diminimalisir. Bahkan warga sipil dapat terhindar dari dampak perang. Masalahnya kemudian, semua itu adalah asumsi konstruktif yang dibangun analis militer pro-industri perang. Kenyataan di lapangan bisa berbeda. Ketika serangan drone yang sudah mengunci target, ternyata tak bisa menurunkan dampak sampingan akibat ledakan. Sasaran drone memang langsung tewas di tempat, namun tidak ada jaminan warga di sekitar target juga tak bisa jadi korban.
Ada tiga bagian dalam buku ini yang memuat 14 artikel penting. Bagian pertama mengulas konsep pengendalian jarak jauh (remoteness/peremotan) yang membeber tulisan enam pakar. Diantaranya, artikel Emily Crawford yang perlu disimak. Artikel ini bertajuk prinsip keunggulan dan perang jarak jauh. Penulis artikel yang juga dosen Universitas Sydney Australia itu menegaskan prinsip perang jarak jauh sesungguhnya bukan hal baru. Sejak manusia menggunakan busur silang untuk menembak musuh, mulai saat itulah perang jarak jauh berlaku. Penemuan senjata api hanyalah memperluas prinsip perang ini. Namun, tingkat ketepatan menembak target tetap menjadi persoalan utama, apalagi pada target yang jauh sekali.
Inilah yang membedakan antara perang di masa lalu dari perang di masa mendatang. Berkat keunggulan teknologi, mengunci target menjadi hal biasa. Penerapan hukum terhadap target harus diikuti keakuratan militer dalam menggunakan peralatan nirawak. Keakuratan obyek ini perlu memperoleh perhatian dalam setiap kali tes yang digelar militer. Tidak boleh sembarangan apalagi asal-asalan. Oleh karena itu, pemakaian drone dalam konteks militer tentu tidak bisa main-main. Begitupula dalam perang siber yang dibedakan dalam dua hal. Pertama adalah serangan ke jejaring komputer. Dan yang kedua adalah upaya eksploitatif jejaring komputer. Tujuan serangan tentu saja untuk menurunkan kapabilitas komputer, sedangkan tujuan eksploitatif justru menggunakan komputer lawan guna mengeruk informasinya. Kedua situasi ini sangat rawan kerusakan dan sangat perlu dicegah melalui aturan-aturan siber yang ketat.
Bagian kedua buku ini menyodorkan empat artikel, yang dua diantaranya menyelami perang drone. Selama ini militer pengguna drone selalu berkilah drone hanyalah alat untuk mempertahankan diri. Walau kenyataan di lapangan menunjukkan serangan drone terjadi bukan pada masa perang, kilah militer itu tak pernah surut. Ketika sorotan ditujukan pada mereka, untuk kesekian kalinya kilah untuk bertahan diri itu mencuat kembali. Kasus Reyaad Khan di Inggris bisa menjadi bahan kajian. Berulangkali (bekas) Perdana Menteri Inggris David Cameron menegaskan Reyaad Khan, warganegara Inggris yang bergabung ISIS, merupakan ancaman potensial.
Reyaad sendiri tak pernah diinterogasi aparat keamanan Inggris terkait tudingan Cameron. Sampai kemudian ia dan warga negara Inggris pendukung ISIS lainnya, Ruhul Amin, tewas diserang drone. Cameron berdalih serangan itu dilakukan demi mempertahankan diri. Tampaknya, kilah mempertahankan diri telah menjadi prinsip hukum aparat kontra-teror. Padahal, hukum pidana Inggris sendiri sesungguhnya tak mengenal ekstra-teritorial, sehingga dalih Cameron itu pun kemudian dipertanyakan banyak pihak. Penulis artikel ini, Nigel D White dan Lydia Davies-Bright, juga mempertanyakannya. Bahkan di akhir bahasan, mereka menilai pemerintah Inggris telah melabrak standar-standar HAM.
Secara keseluruhan, isi buku ini memang layak menjadi rujukan dalam riset-riset hukum di bidang peremotan. Berbagai perspektif yang disajikan, terasa sekali nuansa baru disodorkan para penulisnya. Perubahan demi perubahan dalam ranah teknologi drone serta siber memang perlu terus dicermati, apalagi kemudian terbukti berdampak pada kehidupan manusia.
Oleh: Rosdiansyah
* Peresensi alumni FH Unair, master studi pembangunan ISS, Den Haag, Belanda. Peraih berbagai beasiswa internasional. Kini, periset pada the Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi/JPIP, Surabaya