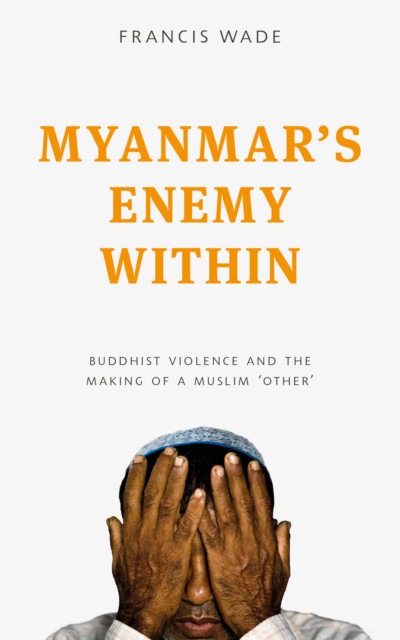Judul Buku : Myanmar’s Enemy Within
Penulis : Francis Wade
Penerbit : Zed Books, UK
Tebal : xiv + 280 halaman
Cetakan : Pertama, 2017
Suaramuslim.net – Myanmar menyita perhatian masyarakat dunia saat ini. Bukan lantaran masa lalunya atau suasana eksotis wilayahnya. Namun, Myanmar merupakan contoh negara yang sedang mempraktikkan genosida. Negeri di samping Thailand itu dikendalikan langsung junta militer yang karakternya primordial serta menumbuhkan sektarianisme.
Jurnalis Inggris, Francis Wade meluangkan banyak waktu di Myanmar guna melacak sejarah negeri bekas koloni Inggris tersebut. Dalam buku ini, Francis mengulas tentang perubahan sikap selama berabad-abad bagaimana mayoritas penduduk Buddha memandang Muslim. Melalui penelusuran historisnya, Francis menyebut peran kolonialisme Inggris di masa lalu dalam ketegangan saat ini, meski demikian ia lebih menekankan pada perkembangan sejak Perang Dunia Kedua tatkala Myanmar (dulu, Burma) meraih kemerdekaan.
Sebagai jurnalis, Francis telah menyuguhkan analisis berimbang, tidak berpihak kepada salah-satu sisi. Adalah fakta sejarah, bahwa proporsi demografis muslim di Myanmar nyaris setara dengan jumlah penduduk beragama Buddha, namun Francis membantah secara implisit bahwa kehadiran muslim yang besar ini berpotensi mengkudeta pemerintahan yang ada. Lokasi geografis serta pengaruh muslim Rohingya di Myanmar merupakan fakta modern yang menjadi dasar bantahan Francis.
Penelitian Francis ini sangat penting. Ia menunjukkan, sebelum kolonisasi, etnisitas begitu cair, guyub, dan kontingen. Raja-raja Rakhine membawa Muslim untuk memperjuangkan mereka, lalu aliansi etnis bergeser. Begitu kolonialis Inggris tiba, dengan semangat mereka melakukan klasifikasi etnis, membekukan lalu lintas pergeseran etnis dan berasumsi bahwa “ras” memiliki karakteristik permanen.
Pemerintahan koloni Inggris mendesain itu guna mempertahankan pengaruhnya ke masyarakat Burma (sebutan Myanmar di masa lalu). Bertahun-tahun sejak 1824, Inggris mengimpor pekerja India untuk dimasukkan ke dalam pemerintahan Burma dan memberi pinjaman uang kepada sejumlah pihak sehingga menggusur elit Bamar. Praktik kolonialis Inggris ini menyebabkan tumbuhnya nasionalisme sempit yang mengesampingkan mereka yang dianggap berkolusi dengan kekuatan kolonial.
Dibanding Indonesia, praktik kolonialis Inggris di Burma ini sangat rawan terjadinya kebangkitan sentimen ras di negeri jajahan. Indonesia dan Burma relatif sama dalam meraih kemerdekaan, namun jalan yang ditempuh oleh elite Indonesia justru berhasil memilih pendekatan inklusif yang memberikan kewarganegaraan kepada banyak kelompok etnis. Indonesia merdeka pada waktu yang sama dengan Burma namun damai, bersatu, demokratis dan jauh lebih majemuk daripada Myanmar. Perbandingan ini tak disentuh secara spesifik oleh Francis, padahal sangat penting sebagai bahan analisis.
Buku ini berisi 11 bab yang saling bertautan antara satu bab dengan bab lainnya. Diawali dengan prolog yang mengupas berbagai kendala serta hambatan dalam menelusuri jejak persoalan di Myanmar. Tentu tidaklah mudah, jika seorang jurnalis asing seperti Francis harus menggali data lapangan di tengah pengawasan intensif aparat rezim junta militer Myanmar.
Pembahasan Francis lalu masuk ke dalam sejarah masa lalu Myanmar di bawah kendali koloni Inggris. Usai merdeka, segregasi sosial warisan kolonial tetap bertahan. Dalam keseharian, memang tidak tampak nyata bagaimana kecurigaan antar etnis itu mewujud, namun dalam arena politik serta kekuasaan, terutama dalam pemerintahan, kecurigaan antar etnis itu jelas sekali. Rezim junta militer Myanmar sudah punya desain politik macam apa yang hendak dipraktekannya di Myanmar. Oleh karena itu, tema utama buku ini terfokus pada militer merebut kekuasaan pada tahun 1962 guna mendorong semangat proyek pembangunan bangsa yang sangat memaksa sekaligus upaya penyeragaman. Keluar dari manuver ini, ujar Francis, terjadilah peningkatan ekstremisme elite Burma yang mendominasi masa transisi Myanmar saat ini, di mana minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki negara telah menderita secara tidak proporsional.
Pencarian Myanmar baru bertumpu di atas gagasan tentang identitas dan kepemilikan yang dimanipulasi dan didorong ke pusat kehidupan di bawah junta militer Myanmar. Kontestasi politik Myanmar tak pernah lepas dari basis gagasan ini. Myanmar baru dianggap hanya untuk etnik dan ekspresi keagamaan tertentu. Bagi mereka, itulah identitas paling absah untuk Myanmar baru.
Tatkala reformasi meluas setelah 2011, semangat penyeragaman itu lantas diambil oleh berbagai kekuatan sosial Myanmar. Termasuk para petani Buddha, yang mengatakan kepada penulis buku ini, bahwa mereka melakukan penyerbuan pada tahun 2012 ke desa-desa Muslim. Dengan parang dan obor, para petani ini menyerang Rohingya, yang ironinya, para Rohingya ini sebelumnya adalah mantan teman dan rekan bisnis para petani tersebut. Aparat junta militer Myanmar cenderung bersikap layaknya provokator yang berdalih, apa yang terjadi itu bagian dari upaya membangun Myanmar baru. Tentu saja, kaum Rohingya tak tinggal diam, mereka membalas. Terjadi serangan berikutnya oleh para petani Buddha ke kampung-kampung Rohingya. Ratusan orang dibiarkan mati, desa-desa terbakar. Bagi aparat pemerintah, kepolisian Myanmar dan serdadu Myanmar, tak ada lagi hidup damai berdampingan antara etnik Bamar dan Rohingya. Tiada lagi kehidupan koeksisten itu. Yang ada hanyalah, bagaimana caranya melanggengkan kekuasaan serta kendali atas Myanmar, walaupun harus melalui cara kekerasan.
Provokasi kebencian pada Rohingya yang disebarkan aparat keamanan terjadi masif, menyentuh pada keluarga-keluarga petani di tingkat desa. Transisi Myanmar dari junta militer ke kehidupan demokratis belakangan ini ternyata juga tidak berjalan sesuai angan-angan kaum pro-demokrasi. Militansi baru berbahan bakar sektarianisme dan primordialisme yang disemburkan organisasi fasis Myanmar tak bisa dibendung lewat aksi-aksi pro-demokrasi. Kaum Rohingya tetap tak tersentuh kesetaraan apalagi keadilan.
Narasi internasional sarat Islamofobia ikut memacu pertumbuhan ultra-nasionalisme Myanmar. Elit Myanmar yang memperjuangkan perlindungan agama Buddha dan ras Bamar berdalih untuk menghindari pemusnahan atau penyerapan oleh Islam. Narasi ini dihembuskan secara sistematis sehingga menambah bobot primordialisme serta sektarianisme Bamar, yang pada gilirannya memicu kemarahan kelompok-kelompok ekstremis Buddha di Myanmar. Bahkan, salah-satu dasar untuk memelihara sikap Islamofobia ini adalah melalui manipulasi data demografis.
Muslim Rakhine memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi daripada umat Buddha Rakhine. Tapi, menurut Bank Dunia, Muslim Bangladesh memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah daripada Myanmar Buddha. Kondisi sosial ekonomi, termasuk kemiskinan dan status pendidikan, daripada agama lebih relevan dalam menjelaskan tingkat kesuburan yang bervariasi.
Penduduk miskin, pedesaan, tidak berpendidikan cenderung memiliki lebih banyak anak. Sayangnya, Francis tidak menunjukkan bahwa negara bagian Rakhine, dengan ekonomi yang tertekan, cenderung mengekspor pekerja muda Rakhine Buddha ke bagian lain Myanmar, yang menekan pertumbuhan populasi Buddha. Demi menjaga keseimbangan, tulis Francis, militer Myanmar berkepentingan menciptakan “pihak lain” yang berbahaya, meskipun kenyataannya, sedikit bukti sejarah tentang hal ini dalam populasi Muslim Myanmar. Itulah bentuk manipulasi demografis junta Myanmar yang hendak melanggengkan kekuasaan dengan mengorbankan Rohingya.
Namun demikian, ulasan Francis dalam buku ini tetap perlu dikritik, khususnya pada akurasi sejarah Myanmar. Jika dalam buku ini Francis tersirat menyimpulkan desain ketatanegaraan Myanmar sejak tahun 1962 berkaitan pada manipulasi agama, akan tetapi pada kenyataan justru menunjukkan sebaliknya. Junta militer Myanmar yang berkuasa sejak tahun 1962 sampai 1988 justru bertumpu pada sosialisme. Warna rezim junta militer ini jelas sekali sosialisme. Di dalam rezim ini, segala upaya untuk menjadikan agama sebagai bagian dari desain perundangan atau aturan, justru dapat dicegah. Yang terjadi adalah baru pada pemerintahan sipil dimulai sejak 1988. Ekstremisme kelompok-kelompok Buddha kian meningkat dan terjadilah upaya intensif menjadikan Buddha sebagai agama resmi negara. Pada saat yang sama, provokasi anti-Rohingya terus meningkat. Ikatan sosial antar etnis cepat sekali mengendur, lalu naiklah ketegangan sampai konflik etnis mengarah ke genosida.**
Peresensi: Rosdiansyah*
Editor: Muhammad Nashir
*Peresensi alumni FH Unair, master studi pembangunan ISS, Den Haag, Belanda. Peraih beragam beasiswa internasional. Kini, periset pada the Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi/JPIP serta Pusat Kajian Islam dan Peradaban (Puskip), Surabaya.
**Resensi ini pernah naik di laman themetropolitanreviewofbooks.wordpress.com pada tanggal 18 November 2018 dan diposting ulang Suaramuslim.net dengan persetujuan penulis.