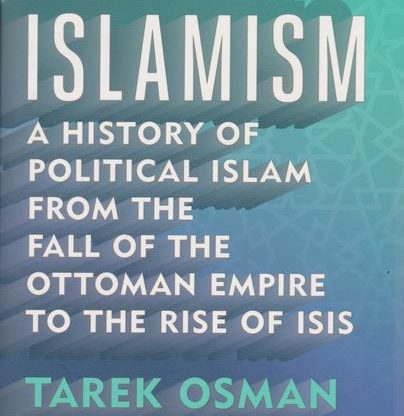Lanjutan Artikel dari Melihat Islamisme Melintas Zaman – Bagian 1
Suaramuslim.net – Sukses berkembang di Mesir, gerakan Ikhwan melebarkan sayap ke Yordania, Suriah dan Iraq. Tahun 1949, Hassan al Banna tewas terbunuh akibat turbulensi politik Mesir. Tak ada sosok kharismatik lagi. Tiga tahun kemudian, Jamal Abdul Nasir mengkudeta Raja Faruk. Jamal mengklaim diri sebagai sekularis, yang segera berkonfrontasi lawan Ikhwan. Namun demikian, hubungan Ikhwan dengan Raja Hussein di Yordania tidaklah sekelam hubungan dengan Jamal. Keharmonisan di Yordania pelan-pelan menjadikan Ikhwan kian besar dan menjadi organisasi paling berpengaruh di negeri bani Hasyim itu. Akan tetapi, pengaruh Ikhwan justru tidak begitu kuat di Maroko. Raja Hassan II tak begitu suka pada kelompok Islamis termasuk Ikhwan. Walau ikut mengusir Prancis dari tanah Maroko (1908-1956), para Islamis pejuang tetap sulit menghirup udara bebas di Maroko. Aparat keamanan Raja Hassan kerap mengintimidasi bahkan mempersekusi para Islamis pada kurun berikutnya. Situasi baru kondusif bagi dakwah Islamisme setelah Raja Muhammad VI, putra Raja Hassan, naik tahta pada 1999. Suasana di Kuwait berbeda lagi. Kelompok Konstitusional Islam yang terinspirasi Ikhwan telah tumbuh beberapa dekade silam. Anggota-anggota kelompok ini menguasai jalur bisnis dan komunitas komersial Kuwait. Pengaruh ikhwan dalam gerakan kaum Islamis juga terlihat di Libya, Aljazair dan Tunisia. Gerakan Annahdah Tunisia yang dimotori Rasyid Ghannaushi menjadi penanda tegas kehadiran kaum Islamis di panggung politik negeri tersebut. Sejumlah intelektual Tunisia kaliber Eropa ikut dalam gerakan ini serta merumuskan taktik gerakan menghadapi kelompok sekular. Mereka telah menyaksikan selama bertahun-tahun negeri dibawah ideologi sekular, ternyata tak membawa perubahan signifikan. Isu politik ini kian menguat tatkala kemenangan kaum Islamis di kotak suara justru dibatalkan rezim militer, seperti yang terjadi di Aljazair. Dan fakta mutakhir menimpa nasib Presiden Mursi yang berlatarbelakang Ikhwan, digulingkan Jenderal Asisi di Mesir.
Tarek juga mengupas perubahan dari budaya Salafi menuju jihadis. Kisah perubahan ini dimulai dengan menampilkan sosok Syaikh Sulaiman al Audah, ulama Wahhabi konservatif Arab Saudi. Tokoh kharismatik ini menentang keras kehadiran pasukan AS yang diundang Kerajaan Saudi Arabia guna menghadapi aneksasi Saddam Hussein atas wilayah Kuwait pada 1992. Sebagai ulama sohor yang mempunyai pengikut ribuan tersebar di seantero jazirah Arab, kritik Syaikh Sulaiman tentu saja sangat diapresiasi pengikutnya. Tatkala pecah gejolak ‘Musim Semi Arab’, Syaikh Sulaiman merupakan pendukung setia gerakan perubahan yang dipelopori kaum muda Arab. Ia kian kondang dan ceramah-ceramahnya di youtube ditonton jutaan pemirsa. Tak perlu diragukan lagi, keintelektualan Syaikh Sulaiman yang luwes serta terbuka pada perubahan merupakan penanda kelahiran salafisme modern, dan berakhirnya Salafisme abad 19, terutama di Mesir dan kawasan Mediterania. Masalah perubahan sesungguhnya bukan barang baru bagi wacana keislaman. Masalah ini sangat lekat pada pemakaian akal (rasionalitas), yang telah digulirkan oleh Jamaluddin al Afghani dan Muhammad Abduh pada dua dekade akhir abad ke-19. Karya kedua tokoh ini sangat menekankan pemakaian akal dalam proses ijtihad, sebagaimana dulu pernah dicontohkan para intelektual muslim abad keemasan peradaban muslim. Walaupun bersentuhan pada filsafat serta kebudayaan Yunani, fakta sejarah menunjukkan produk peradaban Yunani hanyalah sarana, bukan tujuan. Maka, hal serupa juga bisa ditujukan pada modernitas Barat. Produk-produk modernitas hanyalah sarana, yang bisa digunakan kaum muslim untuk kembali menggapai masa keemasan. Oleh karenanya, modernitas bukanlah musuh, namun ia hanyalah sarana. Kaum muslimlah yang ditantang menggunakan akal untuk menyaring modernitas guna menyelesaikan problem-problem internal.
Kaum sekular, khususnya politisi sekular, tidak akan pernah merasa nyaman dari keberadaan kelompok Islamis. Digulingkannya Presiden Mursi di Mesir merupakan fakta atas hal ini. Mursi dan kelompok Ikhwan yang memenangkan Pemilu beberapa tahun silam usai gejolak ‘Musim Semi Arab’ dan lengsernya Husni Mubarak, ternyata tak kuasa menghadapi serangan politik kaum sekular Mesir. Situasi serupa juga terjadi di Tunisia, tatkala partai Islamis Annahdah terus-menerus mengalami perlawanan politik dari gerakan buruh Kiri. Protes kelompok buruh marak. Mereka tak puas atas dominasi partai Annahdah dalam panggung politik Tunisia. Namun sebaliknya, belum ada tawaran nyata kaum sekularis atas penyelesaian persoalan-persoalan publik, sehingga publik Tunisia pun masih belum bisa sepenuhnya bergeser ke kalangan sekularis. Kecuali para mahasiswa Tunisia yang memang sedari awal umumnya menjadi lahan persemaian gagasan-gagasan sekular. Selain itu, elit Arab seperti di Mesir dari Nasser sampai al Sisi, Assad di Suriah, para politisi Aljazair, bahkan pemimpin PLO pasca Yasser Arafat, nyaris seluruhnya merupakan pewaris cara berpikir Arab era liberal, bahwa nasionalisme Arab merupakan satu-satunya ideologi nasional yang melampaui seluruh agama. Seluruh pemimpin kawasan beridentitas nasionalisme Arab ini memakai gagasan liberalisme Arab untuk menggusur ide-ide Islamisme. Bagi mereka, kearaban berada jauh di atas sentimen agama, yang pada gilirannya produk kebijakan mereka pun tak ingin dicampuri oleh nilai-nilai agama manapun, termasuk Islam. Pada derajat tertentu, kasus ini mirip dengan struktur mentalitas oknum-oknum di Indonesia yang sering bercuriga pada kelompok muslim. Selain mereka ini alergi pada simbol-simbol Islam, mereka juga berupaya sekuat tenaga menyumbat mobilitas vertikal ke atas aspirasi muslim atau SDM muslim yang unggul. Oknum-oknum ini berusaha sekuat tenaga mempertentangkan keislaman dengan keindonesiaan. Keislaman diperlawankan pada kebhinekaan, atau keislaman dipertentangkan dengan kepancasilaan. Ini taktik berpolitik kaum sekular yang kenyataannya terjadi dimana-mana, ketika berhadapan dengan muslim.
Di akhir pembahasannya, Tarek menegaskan bahwa persoalan utama dari kaum Islamis yang sangat kuat menggenggam Islamisme kali ini bukan lagi terletak pada bagaimana menghadapi serangan kaum sekularis. Namun, yang terpenting bagi mereka adalah keharusan untuk selalu mendefinisikan ulang makna Islamisme itu sendiri dan bagaimana menyajikannya dalam menjawab tantangan masyarakat. Periode dari 2011 sampai 2013 sebenarnya merupakan peluang bagi kaum Islamis untuk menguasai arena politik kawasan Arab, Mediterania dan Afrika Utara. Akan tetapi, ketiadaan jawaban aplikatif dari paham Islamisme terhadap persoalan nyata masyarakat, maka sejumlah persoalan pun jadi berlarut-larut tak terselesaikan. Walau berbeda dari segi geografis dari wilayah yang disorot Tarek dalam buku ini, sepertinya substansi buku masih relevan untuk diproyeksikan pada kebangkitan gerakan Islamis di Indonesia pasca 2 Desember 2016. Dengan satu syarat, ada keterbukaan dan dialog segar minus prasangka.
Oleh: Rosdiansyah
(Alumni FH Unair, master studi pembangunan ISS, Den Haag, Belanda. Peraih berbagai beasiswa internasional. Kini, periset pada the Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi/JPIP, Surabaya)
*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net